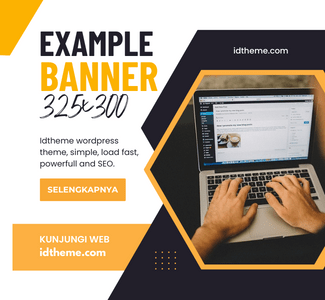Prof.Darmawan di tengah dua seniornya saat di STIP Al-Gazali Ujungpandang masing masing Ir.Pia dan Ir.Nanna.
Makassar, Pattisenews.com:
Jalan menuju pengakuan Profesor memerlukan pendekatan yang bernuansa dan strategis. Maha Guru yang diraih inipun merupakan bukti dedikasi, penelitian, sekaligus pemahaman begitu mendalam selama bertahun tahun, terhadap bidang tertentu.
Profesor Dr.Ir.H.Darmawan,MP–alumni Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIP) Al-Gazali Ujungpandang , angkatan 1986 yang dikukuhkan bersama tiga profesor lainnya masing masing Prof.Ir.Muh.Ikbal Illjas,M.Sc.Ph.D (Kepakaran Ilmu Nutrisi dan Makanan Ikan), Prof.Dr.H.Mauli Kasmi,S.Pi,M.S, (Kepakaran Manajemen Agribisnis Perikanan) dan Prof.Dr.Ir.H.Nursidi Latif,M.Si (Kepakaran Manajemen Perikanan) di Claro Hotel, Rabu 5 Februari 2025.
Saat pengukuhan sebagai Profesor yang mengkhususkan diri dalam hubungan rumit antara karakteristik iklim, potensinya sebagai sumber daya, dan pengembangan komoditas perkebunan, menguraikan strategi utama untuk mencapai keberhasilan tersebut, dengan fokus pada menunjukkan keahlian, penelitian yang berdampak, dan kontribusi yang membentuk masa depan pengembangan komoditas perkebunan. Berikut pandangannya yang dimuat pada bagi ke-4 secara bersambung.
Iklim merupakan salah satu sumberdaya alam yang sangat berpengaruh terhadap pengembangan pertanian dengan berbagai usaha dan pengelolaannya. Keberhasilan pengelolaan sumberdaya lahan untuk usaha budidaya pertanian dalam menghasilkan produksi, memerlukan perencanaan dan program yang disesuaikan dengan daya dukung lahan. Iklim menjadi salah satu sumberdaya yang perlu dikelola sesuai dengan potensi dan daya dukungnya.
Profesor Darmawan kemudian mengurainya dalam tiga bagian, mulai dari potensi wilayah dan pengembangan pertanian perkebunan, dampak iklim terhadap poduktivitas tanaman perkebunan, dan pengelolaan dan pengembangan perkebunan berkelanjutan.
Potensi wilayah dan pengembangan pertanian perkebunan yang dimaksud Prof. Darmawan terlihat jelas pada laporan Badan Statistik Nasional (Mei 2024). Dimana, luas potensi lahan untuk perkebunan adalah 25.789.000,07 ha, potensi ini cukup besar untuk pengembangan tanaman perkebunan dengan berbagai komoditi andalannya.
Komoditi andalan nasional yang dikembangkan, terutama Kelapa Sawit, Kelapa, Karet, Kopi, Kakao, Tebu, Teh dan Tembakau. Sedangkan data potensi lahan untuk pengembangan perkebunan di Sulawesi Selatan (data BPS per Mei 2024), seluas 422.000,4 ha yang merupakan lahan pengembangan beberapa komoditi andalan Sulawesi Selatan yang juga merupakan komoditi andalan nasional seperti Kelapa Sawit, Kelapa, Karet, Kopi, Kakao, Tebu, Teh dan Tembakau.
Luas areal lahan perkebunan yang diusahakan di Indonesia (Data BPS, 2024) hingga akhir tahun 2024), perkebunan kelapa sawit seluas 16,8 juta ha; perkebunan kelapa 3,34 juta ha; perkebunan karet 3,83 juta ha; perkebunan kopi 1,27 juta ha; perkebunan kakao 1,2 juta ha; perkebunan tebu 504,800 ha; perkebunan teh 107.905 ha; dan perkebunan tembakau 191.900 ha.
Potensi produksi dengan luas lahan yang menjadi lokasi pengembangan komoditi perkebunan akan bisa dimaksimalkan, jika kesesuaian iklimnya yang menjadi bagian analisis kesesuaian lahan terpenuhi dengan baik. Karena itu, analisis dan feasibility studi untuk pengembangan komoditi perkebunan ini harus dilakukan dengan matang. Apalagi dengan kondisi iklim saat ini yang terus berubah secara global. Kondisi ini harus dapat diantisipasi dengan mempersiapkan perencanaan yang terukur (Kurniadi, et al. 2024). Data ini diperkuat oleh Yuniasih et al. (2022), bahwa pada rentang waktu tahun 2013-2022 (Arif, Ahmad. 2023), Indonesia mengalami beberapa kali kejadian anomali iklim.
Kondisi iklim normal terjadi pada tahun 2013, 2016, 2017, 2018. El Nino terjadi pada pertengahan tahun 2014 dan 2015 dengan kondisi kekuatan El Nino kuat dan 2019 dengan kondisi kekuatan El Nino lemah, sedangkan pada pertengahan 2020, 2021, dan 2022 mengalami kondisi La Nina lemah hingga sedang, sedangkan kondisi La Nina 2023 dan 2024 termasuk kondisi La Nina sedang hingga kuat.
Kemudian dampak iklim terhadap poduktivitas tanaman perkebunan, Prof. Darmawan menyebutkan, perubahan iklim yang memberikan banyak dampak, menyebabkan perubahan iklim menjadi isu strategis karena persoalan ini dapat mengancam kepentingan nasional suatu bangsa yakni berdampak langsung pada pergeseran musim yang menyulitkan para petani menentukan masa tanam dan masa panen bagi tanaman pertanian (kususnya tanaman semusin).
Selain itu, fluktuasi suhu dan kelembaban udara yang semakin meningkat dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan organisme pengganggu tanaman juga mengalami peningkatan. Secara jelas, pengaruh iklim terhadap sektor pertanian, misalnya perubahantemperatur secara global memicu terjadinya musim kemarau yang berkepanjangan, hujan badai ektrem yang dapat menganggu keberlangsungan ritme pertanian yang berdampak negatif pada pertanian dan perkebunan.
Di antaranya, (1) peningkatan suhu rata-rata yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman; (2) pola curah hujan yang tidak stabil dapat merusak tanaman dan infrastruktur pertanian; (3) penyakit dan hama baru dapat berkembang akibat perubahan iklim; (4) keanekaragaman hayati dapat berkurang akibat perubahan iklim; (5) siklus budidaya tanaman dapat terganggu akibat perubahan pola cuaca; dan (6) ekosistem perkebunan dapat rusak akibat perubahan suhu dan pola curah hujan.
Pada proses budidaya tanaman perkebunan, setiap komoditi memerlukan syarat tumbuh dan cara pengelolaannya secara spesifik. Misalnya saja cara budidaya tanaman kelapa sawit, kelapa, karet, kopi, kakao, tebu, teh dan tembakau memiliki karakteristik pengelolaan yang berbeda-beda. Misalnya pada tanaman kelapa sawit (Siregar, et al. 2021), bahwa penyebaran curah hujan juga merupakan faktor penting untuk perkembangan bunga dan produksi tandan.
Pada umumnya sewaktu musim hujan terbentuk lebih banyak bunga betina, sedang pada musim kemarau terbentuk lebih banyak bunga jantan (Turner, 1978). Sebagian besar dari produksi tandan pada setiap tahun berjalan sebenarnya sangat ditentukan oleh keadaan 24 – 42 bulan sebelumnya. Keadaan ini disebabkan adanya hubungan yang erat antara curah hujan maupun radiasi matahari dengan sex ratio (Hartley, 1977).
Penyebaran curah hujan yang mencolok terdapat pada perkebunan kelapa sawit di Afrika Barat dimana selama 2 – 4 bulan terjadi kekeringan, cenderung untuk mempertajam fluktuasi produksi tandan buah dari tahun ke tahun dengan hasil yang sangat rendah secara siklikal terjadi setiap 4 – 6 tahun (Ng, 1972).
Pada tanaman kopi, rendahnya produktivitas kopi merupakan salah satu permasalahan utama dalam sistem produksi kopi Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah akibat dari variabilitas dan perubahan iklim, disamping karena perawatan kopi yang tidak dilakukan secara optimal.
Terutama terhadap tidak diperhatikannya fase fenologi kopi pada proses budidayanya. Berbagai teknologi adaptasi kopi sudah banyak dihasilkan, namun langkah adaptasi dengan memanfaatkan prakiraan iklim dalam bentuk penyesuian kegiatan budidaya dengan fase fenologi atau disebut sebagai kalender budidaya belum dikembangkan dengan baik.
Karena itu, perlu pengembangan kalender budidaya kopi sebagai bentuk strategi adaptasi dan peningkatan produktivitas serta potensi dan tantangan pengembangannya (Servina, et. al. 2020). Terdapat fase kritis yang sangat menentukan produksi kopi (Tabel 2). Sebagai contoh titik kritis untuk pembentukan buah adalah akhir fase kedua, dimana saat itu dibutuhkan periode kering untuk pembentukan bunga dan setelahnya harus diikuti oleh periode basah pada awal periode ketiga (Siregar, et al. 2021).
Periode kering dapat diinduksi oleh pembatasan kelengasan tanah atau melalui peningkatan defisit saturasi daun. Saturasi defisit adalah perbedaan tekanan saturasi antar daun dan tekanan saturasi di udara, sedangkan periode basah dapat diinduksi dari curah hujan atau irigasi.
De Camargo dan De Camargo (2001) menyebutkan bahwa terdapat enam fase dalam siklus produksi kopi. Dua fase pertama adalah fase vegetatif. Fase pertama adalah pembentukan tunas dan fase kedua adalah maturasi dan dormansi (istirahat).
Selanjutnya fase ketiga ditandai dengan pembungaan, fase keempat pembentukan buah, fase kelima pematangan buah, dan fase keenam adalah fase istirahat. Setiap fase ini membutuhkan kondisi mikroklimat yang berbeda dan kebutuhan air yang berbeda pula. Seperti pada Tabel 2 di atas, contoh siklus fenologi kopi yang diidentifikasi oleh De Camargo dan De Camargo (2001) untuk kopi di wilayah Brazil.
Secara jelas dampak dari perubahan iklim terhadap komoditi tanaman kakao dapat dilihat, bahwa saat bulan defisit menjadi permasalahan ketersediaan air pada tanaman kakao yang secara umum terjadi pada bulan April−September pada wilayah pantai barat Sulawesi Selatan dan Oktober – Maret pada wilayah pantai timur Sulawesi Selatan.
Kebutuhan air tanaman kakao sebesar 1298 mm tahun-1. Peningkatan suhu sebesar 0,5 0,7; dan 1 ⸰C menyebabkan peningkatan kebutuhan airmenjadi 1312 mm tahun-1, 1321 mm tahun-1, dan 1328 mm tahun-1. Nilai ETp lebih besar18dibandingkan AE pada lokasi penelitian yang menyebabkan reduksi produksi kakao (Afifah, 2022).
Reduksi produksi meningkat pada setiap peningkatan suhu yang dikombinasikan dengan penurunan curah hujan, sehingga semakin besar peningkatan dan penurunan curah hujan maka ketersediaan air dalam tanah berkurang. Menurut Sakiroh et. al. (2015), kekeringan dapat menurunkan mengakibatkan kematian tanaman kakao belum menghasilkan (TBM) maupun tanaman kakao menghasilkan (TM).
Sementara pengelolaan dan pengembangan perkebunan berkelanjutan, Prof.Darmawan mengaku, data potensi luas lahan untuk perkebunan sekitar 25.7 juta ha (secara nasional) dan Sulawesi Selatan 422.000 ribu ha, memerlukan pengelolaan yang berkelanjutan, meskipun kondisi perubahan iklim terus terjadi, baik secara global maupun secara local (Darmawan dan Mutalib, 2024).
Caranya adalah bahwa persiapan perencanaan, mengembangkan komoditi yang adaptif terhadap kondisi lingkungan tempat pengembangannya dengan memperhatikan keberlanjutan lahan dan keberlanjutan produksi, kajian-kajian dan penelitian yang mendukung serta implementasi teknologi dalam pengelolaan lahan perkebunan yang ramah lingkungan.
Bahkan pendampingan yang dilakukan mulai dari on farm (pada petani kakao dan kelompoknya) hingga pada off farm (pengolahan dengan berbagai produk olahan) yang di pasarkan. Pendampingan pengolahan bersama mitra juga sudah menjadi perhatian pemerintah melalui program Matching Fund (MF) untuk terus dikembangkan.
Kegiatan penelitian dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan pengelolaan perkebunan telah banyak dilakukan, seperti pada tanaman kakao melalui integrasi dengan ternak “zero waste”, pengembangan pembibitan dengan memanfaatkan pupuk organik hayati (POH) dalam menyiapkan bibit tanaman perkebunan (kakao dan kopi), implementasi Good Agricultural Practices (GAP) dengan menerapkan penyehatan tanah dan lingkungan minim bahan kimia.
Penelitian seperti ini malah mendapatkan perhatian pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Kemendikti Ristek) dengan skema penelitian produk vokasi (P2V) pada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Vokasi), seperti pada Gambar 7a, 7b, dan Gambar 8).
Demikian juga pengembangan pembibitan tanaman kakao dan kopi (Gambar 8) dengan memanfaatkan Pupuk Organik Hayati (POH) dan pengembangan Kopi Arabika Organik seperti di PT. Sulotco Jaya Abadi di Bolokang Tana Toraja (Gambar 9) dan juga pengembangan tanaman jagung seperti pada Teaching Farm Bulu Dua Politeknik Pertanian Negeri Pangkep di Buludua (Gambar 10), di kabupaten Barru Sulawesi Selatan.
Sebelum mengakhiri pidato pengukuhannya, Prof.Darmawan mengambil kesimpulan bahwa, perubahan Iklim dan fluktuasi cuaca tidak dapat dihindari karena merupakan hukum alam dan menjadi sunnatullah, karena itu perlu dianalisis dan dikelola untuk bisa diadaptasi dalam pengembangan pertanian dan perkebunan.
Sektor pertanian dan perkebunan merupakan sektor vital dalam menyiapkan dan mendukung ketahanan pangan, sehingga pemanfaatan sumberdaya lahan perlu terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 8 milliar manusia di dunia. Dan perlu pengembangan pertanian terus dilakukan dengan cara mengelola melalui pertanian berkelanjutan. (din pattisahusiwa/bersambung)